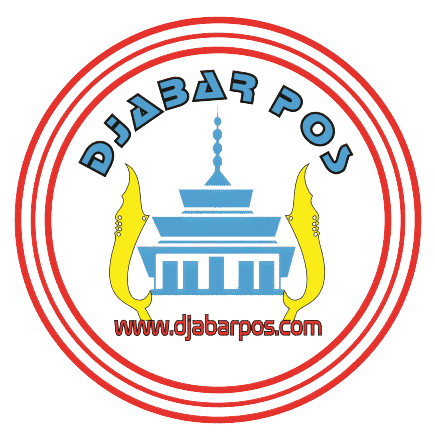Oleh Roni Maulana Arsy (Jurnalis Media Djabar Pos)
Menjelang pesta demokrasi daerah, kita sering menyaksikan kedekatan luar biasa para kontestan dengan insan pers. Para calon kepala daerah menjadikan setiap jengkal langkah dan setiap lontaran gagasan sebagai berita hangat. Mereka berlomba-lomba memikat perhatian media, menjadikan media panggung utama untuk membangun citra dan meraup dukungan elektoral. Telepon genggam mereka seakan tak pernah jauh, selalu sigap merespons pertanyaan, bahkan tak jarang menyapa demi publisitas.
Namun, narasi indah itu acapkali berubah drastis begitu palu pelantikan diketuk.
Ironisnya, politik lokal terus menyajikan fenomena pejabat publik yang bertransformasi dari sosok mudah diakses menjadi figur misterius di balik meja kerjanya. Wali kota, bupati, beserta para wakilnya, yang dulunya hangat dan responsif, kini sulit jurnalis jangkau. Upaya wartawan mengonfirmasi informasi penting seringkali membentur panggilan tak terjawab, pesan tanpa balasan, dan lingkaran kekuasaan yang memblokir akses. Jalinan komunikasi yang dulunya terbuka lebar, kini membeku dalam sunyi birokrasi.
Tentu, publik memahami padatnya agenda pemerintahan. Akan tetapi, kesibukan berlebihan tidak membenarkan isolasi diri dari media. Setidaknya, juru bicara atau bagian humas yang berfungsi optimal dapat menyampaikan informasi. Komunikasi adalah niat baik, bukan sekadar waktu luang.
Fenomena ini bukan hanya merugikan independensi media sebagai pilar keempat demokrasi, melainkan juga merampas hak masyarakat atas informasi akurat dan terpercaya. Media menjalankan fungsi publik, menjembatani aspirasi rakyat dan kebijakan penguasa, bukan melayani kepentingan personal.
Ketika para pejabat menutup pintu komunikasi, mereka sesungguhnya mengunci akses publik terhadap informasi yang seharusnya transparan.
Negara demokrasi kita menjunjung tinggi kebebasan pers sebagai fondasi penting. Media adalah pilar utama penjaga keseimbangan kekuasaan dan pengawal kepentingan publik. Oleh karena itu, setiap pemegang amanah rakyat harus membangun relasi yang sehat dan saling menghormati dengan media. Kemitraan ini harus berlandaskan kesadaran akan urgensi akuntabilitas, bukan sekadar kalkulasi pragmatis menjelang kontestasi politik.
Editorial ini adalah refleksi : jabatan publik bukan hanya kekuasaan dan protokoler, tetapi juga tanggung jawab untuk tetap terbuka, komunikatif, dan menjawab pertanyaan publik melalui media.
Jangan biarkan kedekatan dengan media sekadar taktik kampanye. Media adalah pilar demokrasi esensial, bukan alat peraga politik musiman. Ingat kehangatan saat membutuhkan suara, dan jangan biarkan diri menjelma sosok misterius di balik meja kerja setelah meraih kekuasaan.